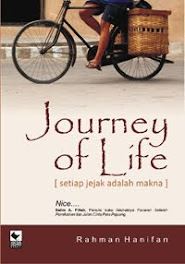Di samping mempersiapkan kebutuhan lebaran, sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan adalah waktu untuk terus-menerus memperbanyak amal. Begitu pula yang di lakukan Bu Endang. Satu hal yang tak pernah dilupakanya; bersedekah. Kepada ibu asli dan ibu mertuanya Bu Endang selalu mengirimkan sejumlah belanjaan. Isinya biasanya berupa kue-kue untuk lebaran ditambah selendang.
Ini mungkin sebuah pemandangan biasa. Banyak orang yang memberi lebih kepada orang tua mereka. Yang tak biasa, Bu Endang tak hanya memberikan belanjaan itu kepada orang tuanya. Menjelang lebaran, minimal enam keluarga mengisi daftar untuk Bu Endang untuk dikirim belanjaan. Dua yang tadi sudah disebut. Dua lagi bude (adik dari ibu aslinya), satu kakak, dan satunya lagi kakak dari suaminya. Seringkali beberapa pihak lain juga mendapat jatah.
Ketika ibu kandung dan ibu mertuanya telah meninggal, Bu Endang tetap meneruskan kebiasaannya kepada beberapa pihak lain yang tadi disebut. Kirimannya hampir selalu sama; kue lebaran di tambah selendang, sarung atau pakaian lainnya. Meski Bu Endang sendiri jarang sekali membeli pakaian baru untuk dirinya. Kalau waktu lebaran Bu Endang mengenakan setelah kebaya baru, paling-paling hadiah dari tempat belanja langganannya.
Untuk ukuran seorang ibu yang tinggal di kampung tertinggal, penghasilan Bu Endang tidaklah banyak. Dari jualan sayur dan kebutuhan sehari-hari, hasil Bu Endang itu barangkali tak lebih dari sepuluh ribu setiap harinya. Sedang suaminya yang tak lagi bekerja. Karena bukan pensiunan, suaminya tentu juga tak lagi memberi nafkah. Bila dihitung-hitung, kebutuhan untuk memberikan belanjaan untuk satu pihak jelas berkali lipat dari hasil dagangnya setiap hari. Hanya saja, Bu Endang masih merasa lebih beruntung secara ekonomi dari pihak-pihak yang disedekahinya minimal setahun sekali itu.
Bu Endang selalu mengajak anak bungsunya yang masih kecil ketika mengantarkan sendiri belanjaan-belanjaan sedekah itu. Ketika Maman, anak bungsunya itu telah menginjak usia SD, dialah yang bertugas untuk mengantar belanjaan itu kepada semua yang berhak. Biasa; Mbak Kromo dan Mbak Somo yang tinggal sendirian, Mbak Karto, Mbah Towi, Bu Diyah dan Bu Roijah. Semua mendapat jatah yang hampir sama.
Kebiasaan itu berlangsung terus. Ketika si Maman telah lulus kuliah, ia masih sempat mengantarkan sedekah yang hampir sama titipan emaknya. Meski kini tinggal tiga pihak yang tersisa, karena tiga lainnya telah meninggal. Tapi tentu, di luar nama-nama wajib tersebut, masih ada pihak-pihak lain yang mendapat jatah sedekah Bu Endang.
Ini hanya satu sepenggal kisah dari seorang ibu di sebuah kampung kecil. Di samping itu tentu lebih banyak lagi kedermawanan Bu Endang, yang tak terkisahkan. Beruntunglah saya mendapat pelajaran ini, karena Bu Endang yang saya ceritakan adalah ibu kandung saya. Sedang si Maman, tentulah saya sendiri.