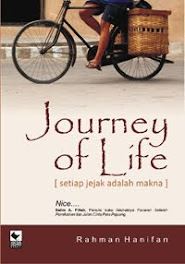Rame orang pasar, berdesing-desing. Sayup-sayup gedebugan - Inul lagi ngebor di pojok sana - dari penjual VCD bajakan. Bus besar kecil, motor, ontel, becak, grobak, pejalan kaki, orang gila, mahasiswa, anak sekolah, preman, banci, pengemis, orang kesasar; lalu lalang. Asap rokok mengepul. Telentang, dua kaki selonjor ke atas. Sesekali melongok kanan kiri, mengapali bus antar kota yang berhenti. Empat jam sudah dia di situ. Lelah menunggu hidup hari ini. Pak Kirman pasrah. Siul, campur sari, selang-seling tebaran asap. Prasasat koyo ngenteni udane mongso ketigo…..
Bus Jakartanan berhenti. Tiga becak balapan, yang dua tabrak-menabrak. Meloncat. Becak ditinggal, kejar orang turun dari bus. Tukang ojek ikut ngebut, nyerobot. Ternyata sudah dijemput pake mobil. Pak Kirman melongo, tapi beruntung. Target lain datang dari pasar.
“Mbecak den?”
“Perum Taman Sari Pak.”
“Iya’ sip.” Pak Kirman meloncat. Sedel becak halus mulus, sebelas tahun tergerus pantat. Penumpang naik dan pedal digenjot. Anak sekolah ngebut. Wanita gembrot naik ontel menyalami, tetangga, teman sepermainan waktu kecil. Dua polisi lalu lintas lagi main remi di gardu, ongkang-ongkang. Topinya saja dipajang. Bus seukuran rumahnya nekat. Terpaksa berhenti empat detik. Setengah centi dari becaknya; Wush…! “Djuancuk! Sopir guendeng!”
Seperempat jam sampai tujuan. Penumpang turun, mata merah kelilipen. Debu kota tak pernah kompromi. “Berapa Pak?”
“Empat ribu Den.”
“Ni lima ribu, nggak usah kembali.”
“Matur nuwun Den. Matur nuwun.”
Gaya orang rada elit. Biasanya kalo ada yang mau naik becak nanya harga dulu, kecuali langganan. Habis itu nawar. Harga lima ribu ditawar seribu lima ratus, emang rongsokan?! Tiga tahun tak pernah naik harga. Tak ada alasan harga premium melambung. Justru untung, menang saing dikit sama ojek. Biaya kaki, paling pijet, setengah tahun sekali. Tak ada biaya amortisasi buat kempol yang mulai kendor dan boyok yang mulai bengkok.
Jam lima sore Pak Kirman cabut. Lelah habis peluh. Daki-daki membunuh, memaksa orang membuang hidung. Becak diparkir, masuk rumah, baju dilempar. Pak Kirman kembali telentang. Kali ini di amben. Nikmat.
Bu Kirman masak sayur terong tambal sambel trasi. Nasi liwetan tadi pagi masih separo, tapi beras ludes. Hari ini Pak tak bawa duit berarti besok puasa. Utang di toko sebelah terkumpul tiga belas ribu. Tambal sulam, tak pernah lunas.
“Gawekno kopi Bune!”
“Gak punya Pakne, sudah habis.”
“Ni duit, beli di warung sebalah. Sekalian beras buat besok. Terus jangan lupa, kretek dua biji.”
“Rokok mulu dipikir! Sini duwite! Parune kumat kapokmu!”
“Biarin, mati sekalian juga tak apa.”
“Pakne masuk neraka aku juga nggak bakal nangis. Tapi aku? Rini anakmu? Mau makan apa? Tega Pakne mati? Iya kalau langsung mati, kalau harus opname dulu tujuh minggu, siap yang mau bayar?”
Dua tahun lalu Pak Kirman pingsan saat nggenjot becak. Di bawa ke rumah sakit, paru bocor. Habis dua juta dibayar adiknya satu setengah. Sisinya dicicil. Tobat dua minggu nggak ngebul. Selanjutnya biasa. Malah tambah banter. Sehari sembilan lencer; tentu kalau lagi ada duit.
******
“Tanggal sepuluh paling telat bayar SPP Pak. Sudah nunggak dua bulan, Rini malu.”
“Belum ada Rin, pijem bulekmu dulu sono!”
“Pinjem-pijem! Malu Pak!”
“Ya sudah, suruh makmu yang pinjem sono!”
“Utang dua bulan lalu tujuh puluh ribu belum dibaliin Pakne. Pinjem sendiri sono kalo gak malu.” Teriak Bu Kirman dari dapur.
“Yo wis, dongakno wae mugo-mugo rejekin banter sitik.”
“Tanggal sepuluh yo Pak, tiga hari lagi. Sembilan puluh ribu buat tiga bulan. Rini berangkat sekolah dulu.”
“Yo wis sono, hati-hati.”
Gundah yang biasa, tak pernah henti, masalah duit. Simpenan di bawah bantal cuma dua puluh ribu. Kalau hari ini dapat sepuluh ribu, berarti besoknya harus dapat enam puluh. Kalau hari ini nggak dapat apa-apa, besok harus dapat tujuh puluh. Ajaib. Sampai kaki putus nggak bakalan bisa. Sebelas tahun narik becak nggak pernah dapat enam puluh ribu dalam sehari. Paling banter lima pulu ribu. Itu pun karena disewa turis, keliling kota seharian bareng dua saingan sekaligus teman ngobrolnya, Pak Hernawan dan Bejo. Pulang-pulang pijet, bayar lima belas ribu. Besoknya cuma bisa ngetem setengah hari.
Jam tujuh pagi Pak Kirman berangkat. Hari ini harus rela ngetem lebih lama. Plus doa. Bagaimanapun juga kepentingan anak nomor satu. Bisa lulus SMK pasti bangga luar biasa. Anak tetangga masih ada yang mentok sampai kelas satu SMP, nggak kuat bayar. Kalau perlu syukuran, buat tumpeng sama gudangan. Kasih telor dua dibagi enam belas.
Pak Kirman dihukum anaknya sendiri. Seharian cuma ngebul dua lencer. Eman-eman duit buat beli rokok. Megap-megap saking pengen. Ditahan. Waktu pulang nggak kuat, beli satu lagi. Teman paling setia sejak disunat; rokok itu. Hari ini lima belas ribu lumayan. Dikurangi buat rokok seribu dua ratus, buat beras dan sayur enam ribu enam ratus, sisa tujuh ribu dua ratus.
*******
Besok pagi deadline dari Rini, anaknya. Bayar buat sebulan aja ngutang, buat tiga bulan sekaligus bagaimana caranya. Terpaksa Pak Kirman ngetem lagi malam ini. Satu hal yang sudah lama tak dilakukannya, semenjak parunya bocor. Udara malam di luar terasa ngeri, bikin takut mati. Namanya juga terpaksa. Hasil siang tadi setelah dikurangi beras dan rokok cuma lima ribu tiga ratus. Total tabungan berarti tiga puluh dua ribu lima ratus. Baru cukup buat satu bulan. Asumsinya esok lusa nggak usah makan.
Malam kian sunyi. Orang pacaran pada pulang. Pegawai kantoran sudah lelap. Orang gila tidur di emperan. Supermarket, toko kelontong, bengkel, rental komputer, mi ayam, bakso, nasi goreng, tempe penyet, semua pada tutup. Kecuali angkringan dan burjo masih buka. Warnet juga masih banyak pengunjung; anak-anak gila ketagihan gambar orang telanjang. Grobak-grobak dorong membikin bunyi; srek-srek.
Dingin, sepi. Jaket dan sarung lupa dibawa. Pak Kirman meringkuk. Bintang gemerlip, rembulan nampak separo. Gemerincing penjual sate lewat. Sesekali mobil dan motor menderum. Jam dua belas malam penumpang pertama. Pegawai negeri pulang dari Jakarta, masih pake baju dinas. Satu tas besar dijinjing, satu lagi di cangklongan. Jelas bukan preman iseng.
“Ke mana njih?”
“Jalan Sri Wedari, habis Taman Sari.”
Hapal betul jalan. Hari ini saja sudah dua kali PP lewat jalan yang sama. Penumpang Pak Kirman memang kebanyakan dari Perum Taman Sari. Dan malam ini terasa berat. Kaki linu, boyok pegel-pegel, kepala sedikit senut-senut, dan nafas kian pendek, sengal-sengal. Kalau bukan karena anak, sudah nglempus pake selimut. Makin lama nggak kuat; ngos-ngosan, sesek. “Tobat, tobat. Rokok keparat!” Masih satu biji di telinga, sisa tadi siang. Diambil lalu di lempar. Dan gdebuk!
“Loh Pak, Pak, kenapa Pak? We, ladalah, tibo.”
Penumpang itu turun. “Pak, Pak kenapa Pak? Loh Pak jangan mati Pak! Aduh piye tho iki?”
Nafas Pak Kirman dicek. “Aduh mati temenan. Ngrepoti wae, mati kok ya nggak nunggu nyampe rumah.”
Pak Kirman diangkat ke becak. Penumpang gantian nggenjot. Balik arah, sempoyongan, ke RSUD. UGD buka.
Pagi harinya ribut. Orang rumah dapat kabar dari Pak Yulianto, penumpang semalam. Rini nangis-nagis, mengutuk diri, mengguyur bantal. Tetangga berdatangan, bikin gaduh. Lima orang dari kampung sebelah, mau layat. Bu Kirman puyeng, “We alah Pakne, disuruh nggak usah berangkat kok ya nekat.”
Jam sepuluh pagi kumpul di rumah sakit. Bu Kirman, Rini, Paijo dan Lastri. Dua yang terakhir adik dan ipar Pak Kirman. Pak Kirmannya nggak mati, semalam cuma pingsan. Hidungnya dipasang selang. Dari semalam sudah habis tiga tabung. Tobat!
“Pakne, Pekne, untung masih ketulungan.”
“Yo wis nasib Bune.”
******
Besok paginya Pak Kirman sudah boleh pulang. Seluruh biaya dibayar Paijo. Plus sembilan puluh ribu buat SPP Rini. Libur narik becak sudah tentu. Siang-siang lemes, dan….
“Bune, tukokno rokok selencer wae!”
2 Agustus 08, kangen Jogja.
 Inilah buku pertamaku. Agak culun-culun dikit, tapi tetep keren. N’ yang paling penting, buku ini telah merubah hidupku. Ternyata aku bisa juga jadi penulis, satu hal yang hingga lulus kuliah gak pernah terpikir olehku.
Inilah buku pertamaku. Agak culun-culun dikit, tapi tetep keren. N’ yang paling penting, buku ini telah merubah hidupku. Ternyata aku bisa juga jadi penulis, satu hal yang hingga lulus kuliah gak pernah terpikir olehku.